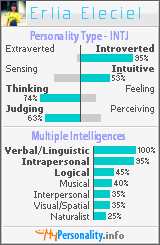Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Proyek Menulis Letters of Happiness:
Link to nulisbuku's article here
__________
Fiction in Fact
“Everything is quiet.
Then a voice calls you, pulling you back to the dream.
Is this a fiction or fact?”
☆ ☆ ☆
Dia berhenti menulis dan membaca ulang hasil tulisannya sendiri untuk beberapa detik dalam diam. Merasa tidak puas, dia merobek kertas tersebut dari buku catatan kemudian membuangnya ke dalam tong sampah di sudut ruangan.
“Apa yang sebenarnya sedang aku lakukan?” dia mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. “Sadar, Arcelio, kau tidak bisa bermimpi selamanya.”
“Tentu saja tidak bisa,” seseorang meninju lengannya pelan sebelum duduk di sampingnya. “Yang benar saja, Cel. Kita ini sedang di Bali, the Paradise Island. Kau seharusnya bersenang-senang di pantai, bukannya sibuk dengan dirimu sendiri di kamar seperti ini. Ayolah, Cel.”
Arcelio berdiri dan melemparkan badannya di atas ranjang, memejamkan mata sambil bergumam, “Pergilah duluan sendiri kalau kau mau, Wynn. Aku masih perlu waktu untuk mencari inspirasi. Aku tidak bisa berkonsentrasi di tengah keramaian.”
Wynn melipat tangannya dan berkomentar pelan, “Jangan terlalu lama di dunia imajinasimu. Aku tahu kau ingin mempertahankan reputasimu tapi kau per-“
“I know what I’m doing. Thank you,” potong Arcelio tajam. “I’m all good.”
Dia mendengar suara pintu kamar hotel ditutup, tanda bahwa Wynn sudah menyerah meyakinkan dirinya untuk menikmati liburan seminggu di Pulau Dewata bersama teman-teman mereka sejak SMA yang ingin melepas penat dari bekerja.
Arcelio berbeda. Dia justru tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencoba mencari apa yang tidak bisa orang lain pahami.
Dia tidak benar-benar tidur. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya Arcelio memutuskan keluar dari hotel untuk menghirup udara segar. Tanpa menetapkan tujuan, ia membiarkan kakinya melangkah entah ke mana, melewati para turis yang berlalu lalang, sampai akhirnya ia tiba di dekat pantai.
Matanya memandang lurus ke langit tak berujung, seolah-olah jika ia terus menatapnya, akan ada yang muncul dari sana. Imajinasinya terhenti saat sebuah bola plastik berwarna merah beradu dengan kepalanya.
“Ouch. Sorry!”
Arcelio mengusap bagian kepalanya yang terkena bola, menggertakkan gigi untuk menahan emosinya memarahi si pelempar bola. Seorang pemuda yang kurang lebih seumuran dengannya menghampiri dengan senyum lebar, “Sorry, kecelakaan kecil. You’re okay?”
Rasa kesalnya menguap dengan cepat, digantikan perasaan familiar yang tidak bisa dia deskripsikan. Arcelio merasa pernah bertemu dengan pemuda ini sebelumnya. Ia tidak ingat kapan atau di mana tapi ia yakin pernah melihatnya. Kata-kata berikutnya meluncur begitu saja dari mulut Arcelio, “Siapa kau?”
Pemuda itu mengangkat alisnya namun bukan ekspresi bingung yang ia tunjukkan. Bahkan, lebih tepatnya, ia terlihat senang diberi pertanyaan tersebut, “Alden. Namaku Alden. Kau pasti Arcelio kan?”
Alden memungut bola yang jatuh dengan senyum puas, “Your first book is a best-seller last year. Ceritanya bisa dinikmati oleh pembaca pria maupun wanita. Adikku sangat menyukai bukumu.”
Pujiannya hanya seperti dengungan di telinga Arcelio. Otaknya terus bekerja, mencoba mengingat di mana dia pernah bertemu Alden. Meskipun mereka baru berkenalan, rasanya ini bukan pertemuan pertama mereka.
“Apa yang sedang kau lakukan di Bali?” Alden memecah keheningan, memutar bola dengan jari telunjuknya sebagai poros. “Liburan? Pekerjaan? Mencari inspirasi?”
Tidak ada jawaban.
“Kau tahu…,” Alden memegang bola dengan kedua tangannya, “…bukankah semua ini terasa familiar?”
Belum sempat Arcelio menanggapinya, seorang gadis dengan rambut sebahu memanggil nama Alden. Mungkin ini hanya perasaannya, tapi Arcelio merasa gadis itu tidak menyukainya. Paling tidak tatapan matanya yang dingin menyiratkan seperti itu.
“Oh, Nadia. Hei, ini pengarang favoritmu! Kau tidak mau berfoto dengannya?” tanya Alden santai, menoleh ke arah Arcelio. “Ini saudara kembarku, Nadia. Aku tahu, kami tidak mirip. Oh ya, Dia penggemarmu!”
Nadia menarik lengan Alden pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, “Yang lain menunggumu. Ayo pergi.”
“Okay,” Alden menanggapi. “I’ll see you again, Cel.”
“Tunggu seben-“
Arcelio ingin menghentikan Alden agar dirinya bisa mengingat baik-baik apakah mereka pernah bertemu atau tidak, namun Nadia menghentikannya dengan ekspresi serius, “Kembalilah ke duniamu.”
“Apa aku mengenalnya?” pertanyaan Arcelio terdengar konyol tetapi itulah yang ingin ia tanyakan kepada Nadia. Dia merasa Nadia bisa memberinya jawaban.
Saudara kembar Alden menghentikan langkahnya lalu, tanpa melihat ke arah Arcelio, dia menjawab, “Berharaplah kau mengenalnya.”
☆ ☆ ☆
“I was wondering.
Should I just stay in the fiction, where everything feels better than the reality?”
☆ ☆ ☆
“Oh, what a surprise to see you here again. Masih mencari inspirasi?”
Itulah pertanyaan Alden saat menemukan Arcelio di tempat yang sama persis dengan sebelumnya. Hanya saja kali ini Arcelio sedang menggenggam sebuah pena dan buku catatan kecil. Dia selalu membawanya agar bisa mencatat inspirasi apapun yang muncul di benaknya. Sebaik apapun ingatannya, tulisan adalah jaminan baginya untuk memori manusia yang terbatas.
Alden menghampiri sang penulis yang sibuk menyimpan buku catatan di kantongnya, menunjukkan minat untuk memancing pembicaraan, “Apa kabar buku keduamu?”
Sebuah perasaan tidak senang menyelimuti hati Arcelio. Dia tidak mengerti kenapa ia merasa tersinggung dengan pertanyaan orang asing yang baru ia temui itu. Paling tidak dia merasa baru bertemu dengannya.
“Writer’s block?” tanya Alden tanpa basa-basi. Dia tertawa seolah menyiratkan dia tidak ada maksud menyindir Arcelio. “Buku pertamamu, Fiction in Fact, memang best-seller. Kumpulan cerita pendek yang realistis dan berhasil memenangkan hati banyak orang karena mereka bisa menempatkan diri mereka sebagai karaktermu. The opening story is the most favorite one. Kau tahu kan?”
Arcelio tahu.
Dia seharusnya tahu.
Namun dia tidak ingat apa judulnya.
☆ ☆ ☆
“Ke arah sini,” Alden memberi tanda agar Arcelio mengikutinya. “Tempat yang menarik bukan?”
Mungkin rasa penasaran seorang penulis yang mendorong Arcelio mengikuti Alden saat dia berkata ada hal yang ingin ia tunjukkan. Mungkin rasa penasaran akan Alden yang tampak familiar yang membuat Arcelio mendengarkannya seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama.
Keduanya berjalan di atas pasir pantai, melewati sebuah kapal kayu dan beberapa rumah pohon yang didesain sedemikian rupa. Ada beberapa anak kecil yang sedang tertawa senang. Dua di antaranya mengangkat kotak yang menyerupai peti harta karun. Mereka mengenakan kaos hitam dan celana pendek, tampak girang saat seorang pria berkata pada mereka, “Oke, masih ada satu harta karun lagi!”
Di sisi lain, ada sekitar selusin orang seumurannya yang terbagi menjadi dua lingkaran. Mereka semua memejamkan mata, mendengarkan instruksi seorang pria yang berdiri di antara kedua lingkaran manusia. Di dekat mereka, ada kumpulan kayu yang tampaknya disiapkan untuk api unggun. Tawa ceria terdengar dari mereka saat aba-aba permainan dimulai.
“The Pirates Bay,” kata Alden singkat, kembali mendapat perhatian dari Arcelio. “Nama tempat ini. Selain bisa menikmati makanan di tepi pantai, di sini juga banyak hal menarik yang bisa dicoba. Anak-anak bisa bermain sebagai bajak laut. Orang dewasa bisa mencoba aktivitas outbond beramai-ramai. Biasanya acara ditutup dengan makan malam bersama setelah foto menjelang sunset.”
“Ya, aku tahu,” jawaban itu meluncur begitu saja dari mulut Arcelio.
Dia mendekap mulut, terkejut dengan kata-katanya sendiri. Sebaliknya, Alden justru tersenyum, “Begitu? Syukurlah kalau kau ingat.”
Tidak ada yang bicara lagi sampai mereka berdua tiba persis di tepi pantai, di mana sesekali air laut menggelitik kaki mereka. Warna jingga menghias langit di saat matahari bersiap menyembunyikan dirinya untuk hari ini. Keheningan mengisi beberapa menit berikutnya tetapi Arcelio tidak merasa aneh ataupun canggung.
Dia merasa tenang dan damai.
☆ ☆ ☆
“When I am there, my friends are invisible.
When I go to hide, my friends are there.
Find me.”
☆ ☆ ☆
Mata Arcelio membelalak saat Alden mengucapkan teka-teki yang melekat di ingatannya. Dengan senyum di wajahnya, Alden menunggu respon tanpa mengucapkan apapun setelahnya. Dia bukan menunggu jawaban teka-teki misterius. Dia menunggu sesuatu yang lain.
Dia menunggu Arcelio mengingat.
Arcelio pernah mendengarnya. Dia pernah membacanya. Dia pernah menulisnya.
Itu adalah teka-teki yang ia tulis di cerita pendek pertamanya.
“Sunset,” Alden memberitahu jawabannya, menunjuk ke arah matahari yang mulai menghilang di ufuk barat. “Ketika matahari bersinar, kita tidak bisa melihat bintang. Saat matahari perlahan menghilang, tenggelam dan digantikan bulan, bintang-bintang pun terlihat. Itu kata-kataku untukmu tiga tahun lalu.”
“You found me here, Cel.”
Kepala Arcelio seperti berputar. Rasanya seperti ada yang mengguncang-guncangnya dengan keras. Dia merasa kesulitan bernafas. Memejamkan matanya, bergumam tentang sakit kepalanya, mendadak Arcelio sadar bahwa segala sesuatunya terlalu hening untuk lokasi pantai di Bali.
Ia membuka matanya dan menemukan bahwa hanya ada dirinya dan Alden. Semua keramaian di The Pirates Bay dan turis di pantai menghilang entah ke mana. Waktu seolah terhenti karena matahari yang seharusnya sudah bersembunyi masih tetap tampak jelas di penghujung langit. Rasa sakit Arcelio pun hilang perlahan.
“Aku punya sebuah cerita lucu,” Alden memulai topik pembicaraan. “Tiga tahun lalu aku pergi ke Bali dengan saudara kembarku setelah memenangkan undian. Aku bertemu dengan seorang pria pendiam yang perfeksionis dan keras kepala. Dia datang dengan orang-orang kantornya. Mereka baru saja selesai bermain di The Pirates Bay ketika aku kebetulan lewat untuk mengambil bola yang dilempar Nadia terlalu jauh. Saat itu dia sedang ingin membakar kumpulan kertas ke api unggun yang baru saja dinyalakan.”
“Aku refleks melempar bola itu ke arahnya, membuatnya marah-marah. Tanpa basa-basi, aku mengambil kertas di tangannya dan, tentu saja, dia makin kesal. Sekilas aku bisa membaca bahwa isi kertas itu adalah sebuah cerita. Aku bertanya apakah itu adalah hasil tulisannya dan dia menolak untuk menjawab. Responku sederhana. Jika dia memang tidak menginginkannya, maka lebih baik aku mengambilnya. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia meninjuku!”
Alden tertawa mengingatnya, “Dia kesal sekali tapi aku tetap memegang kertas itu. Ide cemerlang pun muncul di otakku lalu aku menantangnya dengan teka-teki singkat. Jika dia berhasil menemukanku, aku akan mengembalikan kertas itu padanya. Tentu saja dia bersikeras menolak tantanganku yang dia sebut kekanakan. Aku mengabaikannya dan berlari secepat mungkin. Oh iya, kertas itu adalah tulisannya. Setahun setelahnya dia memberitahuku bahwa dia menulis itu karena mendapat inspirasi setelah bermain dengan teman-teman kantornya.”
“Nah, berlanjut ke ceritaku, aku menunggunya di sini keesokan harinya, tempat terdekat dari pertemuan pertama kami. Dia tidak berhasil menemukanku. Begitu juga esoknya lagi. Dia berhasil menemukanku di hari ketiga.”
Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, Alden menyerahkan tumpukan kertas pada Arcelio, “Your writing is good. Kenapa kau ingin membakarnya?”
“Karena semua orang yakin aku lebih cocok bekerja di dunia bisnis,” Arcelio menjawab. Dia tidak berencana menjawab seperti itu tetapi kata-katanya tersusun begitu saja. “Orang tuaku, teman-temanku. Semua orang.”
Alden melipat tangannya dan tertawa, “Apakah menyenangkan menjadi sosok yang orang lain suka tetapi tidak kita sukai? If you like writing, then write.”
Déjà vu. Arcelio tahu dia sudah pernah mengalami percakapan ini sebelumnya.
Sebelum Arcelio bisa mengucapkan kata berikutnya, area sekeliling mereka berubah. Mereka tidak lagi berdiri di tepi pantai. Keduanya berdiri di samping jalan raya, di bawah langit malam dan hujan rintik-rintik yang mulai membasahi jalanan. Alden menunjuk ke seberang mereka dan mereka bisa melihat dua orang sedang berargumen.
Mereka sedang melihat diri mereka sendiri.
“Jangan ganggu aku!” Arcelio menepis tangan Alden kasar. “Bisa-bisanya kau menyebut dirimu sahabatku padahal kau bersenang-senang di saat aku justru tidak bisa menulis?!”
“Hei, hei,” tegur Alden dengan ekspresi kebingungan. “Tenang, Cel. Aku tahu kau sedang kesulitan menuangkan idemu dalam tulisan tapi itu justru yang membuatmu frustasi. Lagipula kau bilang tidak akan bisa fokus bekerja di Bali jadi aku tid-“
Arcelio mendorong Alden, menolak untuk mendengarkannya. Dia menyeberangi jalan persis di saat hujan lebat mengguyur. Ketika itulah ada truk besar yang dikendarai supir yang setengah mengantuk. Supir itu tidak melihat Arcelio tetapi Alden menyadarinya. Dengan sepenuh tenaga, Alden berlari menyelamatkan sahabatnya yang sedang kehilangan konsentrasi.
Semua terjadi terlalu cepat.
Semua gelap dan sunyi.
“Kau merasa terbebani dengan permintaan untuk segera menerbitkan buku kedua. Kau lebih sering mengunci diri di kamar, menolak ajakanku maupun Nadia yang menjadi penggemarmu untuk pergi. Hari itu aku baru pulang dari Bali dan kau marah besar karena hari itu moodmu sedang sangat jelek. Katamu aku berhasil meyakinkan dirimu untuk menulis tetapi hilang begitu saja setelahnya. Kau emosi, aku tahu itu. Aku mengerti. Sayangnya tidak begitu denganmu,” Alden menepuk pundak Arcelio yang terdiam.
“Tapi aku masih menulis…,” bisik Arcelio pelan. “Aku masih menulis. Mengapa aku justru frustasi?”
“Doing what you love is freedom,” tutur Alden dengan senyum lembut, “but loving what you do is happiness. Are you happy now?”
Arcelio tersentak mendengarnya.
Sejak buku pertamanya menjadi best-seller, orang-orang membanjirinya dengan pertanyaan tentang buku keduanya. Tujuannya menulis pun perlahan berubah, dari sekedar keinginan menulis menjadi uang dan ketenaran. Sejak kapan uang menjadi motivasinya dalam menulis? Sejak kapan menulis, hal yang ia sukai, menjadi beban hidup baginya?
“Listen carefully,” Alden memejamkan matanya. “Mereka memanggil kita. Ayo, kita sudah terlalu lama di sini.”
Dia mengulurkan tangannya untuk disambut Arcelio, “Let’s go back.”
☆ ☆ ☆
“Aku masih tidak mengerti,” Nadia melempar pandang kebingungan ke arah kakak kembarnya kemudian ke penulis favoritnya. “Kondisi Arcelio jauh lebih parah darimu, Alden, tapi kau juga koma dalam waktu yang bersamaan dengannya. Bagaimana kalian bisa sadar hanya dengan jeda waktu satu menit?”
Kedua sahabat itu bertukar pandang sebelum tersenyum lebar.
“Seorang sahabat tidak akan hanya menunggu temannya sadar,” kata Alden kalem. “Dia akan datang menghampirinya, menyeretnya kembali ke dunia nyata meskipun dia lebih senang hidup di dunia mimpi.”
Nadia berkacak pinggang, tertawa kecil, “Pantas saja cerita pendek pertamamu menjadi favorit pembaca. Begitu detil dan realistis. Isinya benar-benar tentang pertemuanmu dengan Alden yang menjadi asal mula kau berfokus sebagai penulis kan, Cel?”
“Yes,” tanggap Arcelio, masih ingat betul isi cerita singkat yang ia selesaikan dalam satu jam karena kata-katanya mengalir bergitu saja. Pertemuan pertama mereka, teka-teki Alden, motivasi dari Alden bahwa Arcelio hanya perlu menulis karena ia suka menulis. “Kau ingat judulnya kan, Alden?”
Alden memang tidak terlalu suka membaca tetapi ia tidak mungkin lupa judul cerita pendek sahabatnya yang dijadikan buku, “Tentu saja.”
“Happiness.”
☆ END ☆
Author’s Note:
Arcelio (Spanish): altar of heaven
Alden (Old English): old friend