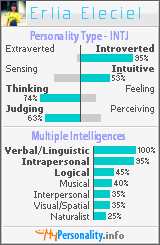Rintik hujan tidak berhenti
membasahi kota sejak pagi.
Matahari sudah terbenam tetapi
belum ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Tidak cukup ringan untuk dilalui
tanpa payung, tidak juga terlalu deras untuk membuat orang-orang berhenti beraktivitas.
Sekelompok pelajar berteduh di
dalam pusat perbelanjaan, menikmati kebersamaan mereka. Pasangan muda masuk ke
dalam kafe, menghabiskan Jumat malam bersama. Anak-anak menanti makan malam
yang disiapkan orang tua mereka sambil menonton televisi.
Ada juga yang menikmati hujan,
berjalan dengan tangan kiri menggenggam payung hitam favoritnya. Kakinya
melangkah perlahan tanpa tujuan pasti dengan tangan kanan berlindung di dalam
kantong jaket. Sesekali dia berhenti dan memandang lurus, seolah ada yang
sedang berdiri menunggunya tidak jauh dari tempat ia berdiri. Beberapa detik
kemudian, ia menjatuhkan pandangannya lagi ke tanah dan melangkah kembali.
Hampir setengah jam berlalu sebelum
akhirnya sebuah bangunan kecil menarik perhatiannya.
“Magia…,” ia membaca pelan papan
nama sederhana yang terpasang di atas pintu kayu berwarna cokelat. Keningnya
mengerut, mencoba mengingat apakah dirinya pernah melewati tempat ini
sebelumnya. Sudah hampir setahun lamanya ia tinggal di area ini tetapi ingatannya
tidak pernah merekam bangunan ini.
Dia berputar, siap untuk melangkah
pergi, tetapi wangi yang tidak asing membuatnya terdiam di tempat. Matanya
terbelalak, tidak percaya dengan penciumannya. Dia memandang lekat-lekat pintu
yang tertutup rapat dan mulai mempertanyakan apakah ini semua hanya
imajinasinya.
Seolah ada yang mendorongnya masuk,
dia menutup payungnya dan membuka pintu tersebut untuk menemukan sebuah toko
kopi di dalamnya. Toko yang sederhana, hanya dilengkapi dengan empat meja
bundar dan delapan kursi, dua meja panjang dengan beberapa botol berisi biji
kopi yang terjejer rapi di atasnya, dan sebuah meja yang terbuat dari kaca di
tengah-tengah ruangan.
Belum sempat dia mempertanyakan
desain ruang yang ganjil ini, suara sang pemilik toko menyapanya ramah, “Halo,
Nona.”
Seorang pria yang mengenakan kemeja
putih rapi tersenyum. Berdiri di balik meja kaca, tangannya sedang menggenggam
sebuah cangkir indah dari porselen. Usianya tampak tidak lebih dari lima puluh
tetapi penerangan toko yang remang membuatnya terlihat lebih tua.
“Selamat datang di Magia,” ia
meletakkan cangkir dengan hati-hati. “Apa yang bisa saya siapkan untuk Anda di
hari Jumat malam ini, Nona?”
“Ah, aku…,” dia terdiam sesaat,
kebingungan memilih kata sebagai jawaban. Dia bahkan tidak tahu tempat apa ini
sebelum masuk ke dalamnya. Dia tidak punya niat sama sekali untuk singgah di
mana pun malam ini. “Maaf, aku tadi ha-“
Pria itu menggeleng pelan, “Jangan
minta maaf, Nona. Kunjunganmu ke Magia bukan sebuah kesalahan.”
Sang pemilik toko berjalan ke salah
satu meja, menarik kursi kosong dan memberi tanda kepada satu-satunya
pengunjung tokonya untuk duduk, “Silahkan, Nona. Saya yakin Anda akan merasa
lebih nyaman menikmati kopi sambil duduk.”
Keraguan pasti tampak begitu jelas
di wajahnya karena percakapan mereka berikutnya dibuka dengan perkenalan diri,
“Nama saya Aisling. Saya pemilik Magia, sebuah toko kopi kecil yang ada bagi
mereka yang membutuhkan. Boleh saya tahu nama Anda, Nona?”
“Ristretta…,” ia memberitahu
namanya dengan pelan. Tangannya menggenggam payung yang masih basah dengan
erat.
Ia beradu pandang dengan Aisling
langsung dan baru tersadarlah dia bahwa bola mata pria itu berwarna ungu. Warna
yang begitu indah, memikat, sekaligus magis.
“Anda bisa meletakkan payung kesayangan
Anda di samping pintu. Mari, duduklah. Saya akan menyiapkan minuman hangat
untuk Anda,” ujar Aisling kalem, masih menunggu Ristretta untuk duduk di kursi
yang telah ia siapkan. “Saya mungkin bukan barista terbaik di dunia ini, tapi
saya yakin bisa menyiapkan minuman yang Anda butuhkan saat ini.”
Ristretta memang merasa agak
kedinginan setelah berjalan tak tentu arah di luar dan dia juga merasa tidak
etis jika mengacuhkan Aisling yang sudah begitu ramah padanya. Dia meletakkan
payung hitamnya di samping pintu kemudian mengangguk pelan ke Aisling. Setelah
Ristretta duduk di kursi, Aisling berdiri di samping meja, siap melayani
tamunya.
“Apakah ada kopi tertentu yang
ingin Anda minum, Nona Ristretta?” tanya Aisling. “Saya bisa membuatkan semua
jenis kopi yang Anda inginkan tetapi, kalau saya boleh memberi saran, ada
baiknya Anda meminta saya membuatkan secangkir kopi yang Anda butuhkan.”
Jari-jari Aisling yang mengenakan
sarung tangan saling bersilang, sebuah gestur yang mengingatkan Ristretta pada
kenangan manis yang justru ingin membuatnya menangis. Atmosfir hangat yang
menyelimuti ruangan membuat Ristretta seperti tercekik oleh kenyataan bahwa
semua ini hanyalah toko kopi milik orang lain, bukan memorinya yang hidup
kembali.
Aisling menatap wanita muda yang
sedang memejamkan matanya dengan tenang seolah sedang membaca pikirannya,
“Ristretta. Nama yang sangat indah. Apakah mungkin nama Anda berasal dari jenis
kopi Ristretto?”
Pertanyaan singkat tersebut
membuatnya tersentak. Ia mendongakkan kepalanya untuk melirik Aisling sebelum
menjawab, “Iya. Ayahku yang memilih nama itu. Ristretto, kopi yang bahkan lebih
pekat daripada Espresso.”
“Kalau begitu, apakah Anda
keberatan jika saya menyiapkan Ristretto untuk Anda?” Aisling memiringkan
kepalanya sedikit, menanti respon dari tamunya. “Tidak butuh waktu lama untuk
menyiapkan secangkir yang sempurna untuk Anda.”
Ristretta tidak langsung menjawab.
Butuh tiga detik untuknya menuturkan apa yang ia pikirkan, “Sudah lebih dari
setahun sejak terakhir aku menyentuh kopi. Apa aku bisa memesan teh atau
minuman lain saja, Tuan Aisling?”
Tidak menunjukkan ekspresi terkejut
sama sekali, Aisling tetap menyunggingkan senyumnya, “Tentu saja bisa, Nona.
Hanya saja, seperti yang saya katakan, saya sangat menyarankan Anda untuk memesan
kopi yang Anda butuhkan.”
Hening sejenak.
“Kopi Toraja…,” pilihan tersebut
terlontar dari bibir Ristretta. “Kopi Toraja Robusta.”
Senyum Aisling semakin merekah
mendengar pilihan tamunya, “Toraja. Pilihan yang sangat menarik, Nona. Mohon
berikan saya waktu untuk menyiapkannya.”
Sang pemilik toko berjalan ke meja
kacanya dan mengambil bahan kopi yang tersimpan di laci meja. Saat melihat
Ristretta mengamatinya, Aisling membuka percakapan kembali, “Tidak banyak tamu
saya yang memilih kopi Toraja. Terlebih lagi yang memiliki nama terinspirasi
oleh kopi.”
Ristretta menghela nafas,
memaksakan senyum tipis, “Ristretto, berasal dari bahasa Italia yang berarti
‘terbatas’. Aku tidak mengerti mengapa ayahku memilih nama ini. Nama yang
sangat membatasi. Nama yang sangat…”
Ia terdiam kembali, menenggelamkan
dirinya dalam ingatan masa kecilnya. Ristretta memejamkan mata, teringat sosok
ayahnya yang selalu menyiapkan kopi setiap pagi. Wangi yang selalu memenuhi
seisi rumah dan membangunkannya dari tidur lelap. Wangi favorit yang sekarang
justru paling ia hindari.
“Ayahku juga seorang barista,” ia
melanjutkan dengan mata yang terpaku pada bangku kosong di seberangnya. “Kopi
Toraja adalah favoritnya. Katanya, itulah kopi yang dia minum saat bertemu
dengan ibuku. Mereka bertemu di Indonesia tiga puluh tahun lalu saat ayahku
sedang mempelajari kopi. Ibuku bekerja paruh waktu di sebuah kafe dan dia yang
mengantarkan kopi pesanan ayahku. Terdengar klise tapi, ya, mereka selalu
menceritakan itu dengan wajah berseri-seri setiap kali ditanya mengapa ayahku
menyukai kopi Toraja.”
“Ah, cerita yang sangat manis,”
Aisling mengangguk, melanjutkan persiapan kopi yang hampir selesai. “Tentu Anda
juga memiliki cukup banyak pengetahuan mengenai kopi, Nona.”
Ristretta memilih untuk tidak menanggapi
pernyataan itu. Matanya kembali terpejam bersamaan dengan kenangan yang
terputar di benaknya bagaikan rekaman film. Kejadian setahun lalu masih begitu
jelas dalam ingatannya seolah semua baru terjadi kemarin.
Suara teriakan ayahnya yang
menggema, memerintahkan Ristretta untuk masuk kembali ke dalam rumah. Nada
suaranya yang meninggi, membalas ayahnya dengan emosi tak terkendali,
menyampaikan betapa kecewa Ristretta karena ayahnya tidak bisa mengerti apa
yang ia inginkan.
“Kalau
Ibu masih ada, dia pasti lebih memahamiku daripada Ayah!”
Kata-kata yang begitu Ristretta
sesali karena pernah ia lontarkan hari itu membuat hatinya seperti tertusuk
kembali oleh ribuan jarum tak terlihat. Dia menelan ludah, berusaha menahan air
mata yang hampir menetes akibat rasa penyesalan.
“Aku pindah ke kota ini tahun lalu
untuk bekerja sebagai penulis lagu. Ayahku tidak setuju. Dia ingin aku
meneruskan usaha kafe miliknya, kafe yang didirikan olehnya dan ibuku. Sejak
ibuku meninggal karena kecelakaan mobil, dia semakin keras kepala. Padahal dulu
dia masih mempertimbangkan permintaanku untuk mengambil karir di dunia musik.
“Kami bertengkar hebat di hari
ulang tahunku. Aku lari dari rumah dan tinggal di rumah sepupuku. Setiap Sabtu,
ayahku akan datang dan membujukku untuk pulang. Setiap kali juga aku akan
mengunci diriku di kamar dan menolak untuk bertemu dengannya. Sungguh
kekanakan, bukan?” Ristretta mengepalkan tangannya dengan kuat.
Sembari Ristretta melanjutkan
cerita hidupnya yang tidak pernah ia ceritakan pada orang lain, Aisling telah
selesai menyeduh kopi Toraja yang dipesan. Ia mengantarkan gelas kopi berwarna
hitam ke meja Ristretta, “Silahkan, Nona. Saya harap kopi seduhan saya sesuai
dengan selera Nona Ristretta.”
Wangi kopi yang familiar kembali
tercium dan air matanya tidak bisa lagi terbendung. Ristretta mulai terisak,
“Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses sebagai penulis lagu. Aku
hanya ingin dia bangga karena aku bisa mengejar mimpiku. Aku hanya…”
Tidak ada yang bicara untuk
beberapa saat. Senyum Aisling sudah menghilang dan matanya memancarkan
kesedihan yang mendalam ketika tamunya melanjutkan, “Setelah dua bulan, dia
berhenti datang untuk membujukku. Dia menulis surat demi surat yang tidak
pernah aku balas. Kemudian surat berhenti dikirim. Aku pikir dia sudah tidak
peduli. Aku pikir…”
Ristretta menyeka air matanya
dengan cepat, “Aku baru merencanakan untuk pulang ke rumah, membuktikan padanya
aku sudah sukses dengan lagu-lagu yang kutulis tapi…”
Lanjutan dari kisahnya tidak dia
sampaikan kepada Aisling. Bahwa kabar dari tetangganya lebih dahulu mencapai
dirinya sebelum ia sempat membeli tiket pulang ke kota kelahirannya. Bahwa ia
tidak akan pernah melihat senyum ayahnya lagi. Bahwa ia tidak akan pernah
mencicipi kopi seduhan yang dibanggakan ayahnya. Bahwa kata-kata terakhirnya
kepada orang yang begitu disayanginya adalah tidak lebih dari emosi sesaat.
Ristretta memendam semua percakapan
yang terjadi di rumah sakit sebagai rahasia.
“Dia
terus menerus menceritakan betapa suksesnya dirimu kepada semua tamu yang
datang ke kafe. Kau harus melihat wajah ayahmu saat kami tahu lagu yang kau
tulis diputar di televisi. Dia sangat bangga, Ris.”
Tetangga ayahnya menyampaikan hal
itu pada Ristretta beberapa jam setelah dia tiba di rumah sakit. Ristretta
sudah berhenti menangis, masih terus mempertanyakan mengapa ayahnya masih
memaksakan dirinya untuk bekerja di musim dingin meskipun dirinya sedang sakit,
masih tidak mengerti mengapa dia tidak merawat dirinya sendiri dengan baik.
“Tidak
mungkin. Dia membenciku. Dia menyerah menghadapiku karena aku terlalu keras
kepala.”
Tanggapan Ristretta yang dingin itu
hanya mendapatkan senyuman hangat dan pertanyaan balik yang membekas di
ingatannya.
“Benarkah
begitu? Apakah dia yang menyerah menghadapimu atau kau yang menyerah terlebih
dahulu, Ris?”
Ayahnya berhenti menulis surat
karena tahu Ristretta baik-baik saja. Setiap hari dia akan memutar lagu yang
ditulis Ristretta di kafe. Setiap kali ada artikel mengenai anaknya, dia akan
mengumpulkannya dan membacanya berkali-kali dengan senyum bangga.
Sehari setelahnya, Ristretta
mengunjungi rumah yang sudah setahun ia tinggalkan dan menangis sepanjang
malam. Di samping kumpulan artikel mengenai kopi yang selalu disimpan ayahnya,
ada scrapbook yang berisi foto-foto
Ristretta sejak bayi hingga dewasa. Ulang tahun pertama, Natal pertama,
kelulusan SMA, wisuda kuliah, hingga foto saat lagu pertama yang Ristretta
tulis dirilis.
Di halaman terakhir, ditempelkan
foto Ristretta dan ayahnya sebulan setelah ibunya meninggal. Ristretta dan
ayahnya duduk berdampingan, memainkan piano. Di pinggir halaman ada tulisan
tangan ayahnya.
“Ris,
kamu berbakat dan Ayah tahu itu.
Ayah
hanya belum siap harus sendirian dalam berbagi kisah tentang kopi yang Ayah
cintai sejak dulu.
Ayah
lupa kamu juga perlu menemukan apa yang kamu cintai.
Saat
kamu kembali, biarkan Ayah menyeduh kopi Toraja favoritmu dan kamu memainkan
piano untuk Ayah.”
Pertanyaan demi pertanyaan
berkecamuk dalam kepala Ristretta. Bagaimana perasaan ayahnya saat dia
berteriak? Apa yang ayahnya pendam saat ia kabur dari rumah? Apa yang ayahnya
pikirkan saat Ristretta menolak bicara padanya? Apa yang ayahnya rasakan karena
anaknya tidak pernah membalas suratnya?
Semua pertanyaan tersebut tidak
akan pernah terjawab.
Ristretta tahu dan itulah alasan mengapa
dia tidak pernah bisa menulis apapun lagi selama setahun terakhir ini.
“Minumlah,” Aisling mendorong gelas
lebih dekat ke gadis yang masih menyeka air matanya dengan tangan kosong.
“Percayalah, ini akan membuatmu merasa lebih baik, Nona.”
Aneh. Sesungguhnya aneh bagi
Ristretta untuk diminta meminum kopi di saat dirinya sedang menangis. Terlebih
oleh orang yang baru ia temui hari ini. Akan tetapi ada sesuatu yang memberikan
ketenangan dalam nada bicara Aisling. Sesuatu yang membuatnya merasa percaya.
Ristretta mencoba menghentikan
tangisnya, menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menempelkan bibirnya di
pinggir gelas. Ia menghirup wangi kopi Toraja yang begitu ia rindukan dengan
mata terpejam kemudian ia menenggaknya.
Hangat.
“Bagaimana rasanya? Pas?”
Mata Ristretta dalam sekejap
terbuka, terkejut mendengar suara yang melontarkan pertanyaan itu. Ia hampir
menjatuhkan gelas yang dipegangnya ketika menemukan seseorang telah duduk di
hadapannya, di kursi yang beberapa detik lalu masih kosong.
“A-A-A-Ayah?!” Ristretta meletakkan
gelas dengan keras, membuat sebagian kopi tumpah. “Apa… A-Apa yang…”
Ayah Ristretta tertawa kecil
melihat reaksi anaknya, “Oh, Ris, kau menumpahkan kopi yang begitu istimewa.”
Dia berdiri, mendekati anaknya
untuk menyentuh pipi Ristretta yang masih dingin, “Kau melewati begitu banyak
rintangan sendirian, Ris. Ayah minta maaf karena tidak bisa mendampingimu
melewatinya.”
Air mata kembali menetes seiring
Ristretta terbata-bata menyampaikan kata-katanya, “Ayah, aku… Aku…”
Dia tidak tahu apakah ini hanya
mimpi, ilusi, imajinasi, ataupun kata lain yang bisa digunakan untuk
menjelaskan situasi yang mustahil ini. Dia hanya tahu sentuhan ayahnya begitu
nyata, begitu hangat.
“Ayah, maafkan aku…,” Ristretta
akhirnya mengucapkan apa yang begitu ingin ia sampaikan pada ayahnya. “Maaf
karena aku menyakitimu dengan kata-kataku. Maaf karena aku meninggalkanmu. Maaf
karena aku tidak mencoba mengerti perasaanmu. Maaf… Ayah, aku menyayangimu.”
Bersamaan dengan ungkapan kasihnya,
Ristretta memeluk ayahnya erat dan menangis seperti anak kecil. Ayahnya menepuk
punggungnya pelan dan berbisik lembut, “Sudah, tidak apa-apa, Ris. Tidak
apa-apa. Ayah juga salah. Berhentilah menyalahkan dirimu, Ris. Kau sudah
menanggung beban yang begitu berat sendirian. Berkaryalah dan buat ayah ibumu
bangga ya.”
Melepaskan pelukannya perlahan,
ayahnya menatap wajah Ristretta dengan senyum penuh kebanggaan seorang ayah,
“Kau sudah dewasa, Ris. Ayah bangga membesarkan putri sehebatmu. Ingat, yang
tidak ada hanyalah wujudnya, tetapi kenangan akan selalu ada. Ingatlah ayah
saat kamu minum kopi, Ris. Ayah selalu ada untukmu.”
“Ayah menyayangimu.”
Ayah Ristretta mengecup kening anak
tunggalnya sebagai salam perpisahan dan, detik berikutnya, Ristretta sudah
terduduk kembali di kursinya dengan Aisling berdiri di sampingnya. Tidak ada
tanda-tanda pernah ada orang lain di ruangan itu. Kopi Toraja yang disiapkan
Aisling pun masih mengepulkan asap.
“Saya rasa kopi Toraja ini cukup
pas dengan selera Nona,” Aisling tersenyum sopan. “Hujan di luar juga sudah
reda. Silahkan menikmati sisa kopi Anda dengan santai, Nona.”
“Tunggu!” Ristretta menghentikan
sang barista dengan cepat. “Aku… Boleh aku bertanya sesuatu?”
Aisling mengangguk, “Tentu saja.”
“Apa… Menurut Anda, mengapa ayahku
memilih nama Ristretta?” pertanyaan yang terdengar begitu acak dan konyol
mungkin tetapi, entah mengapa, Ristretta yakin Aisling bisa menjawabnya.
Pemilik toko Magia itu menjawab
dengan kalem, “Anda telah melakukan apa yang perlu Anda lakukan, jadi sudah
sepantasnya saya juga memberikan jawaban yang Anda butuhkan. Ristretto Espresso
hanya mengambil tiga perempat ons dari shot
untuk menghindari espresso yang pahit, Nona. Ristretto hanya mengambil bagian
yang terbaik. Saya yakin Ayah Anda memberikan nama indah Anda dengan harapan
yang terbaik.”
Beberapa menit setelahnya,
Ristretta sudah menghabiskan kopi Toraja dalam diam tetapi dengan perasaan yang
jauh lebih ringan dari sebelum ia melangkah masuk ke Magia. Ia mengambil
payungnya yang sudah kering dan mengucapkan terima kasih pada Aisling, “Terima
kasih, Tuan. Aku… Aku akan singgah lagi lain kali.”
“Ah, lain kali…,” Aisling mengulang
pelan. “Saya harap saat itu masih lama tapi, jika memang Anda membutuhkan Magia
kembali, saya akan menyambut Anda dengan kopi terbaik.”
Aneh. Semua yang terlihat,
terdengar, dan terjadi di Magia begitu aneh.
Begitu magis.
Tidak lama setelah Ristretta
meninggalkan Magia, lonceng di atas pintu kembali berbunyi, pertanda tamu baru
untuk Aisling.
“Selamat datang di Magia. Apa yang
bisa saya siapkan untuk Anda?”
˜ –
☆ END ☆
— ™
Author's Note:
Magia (Latin): magic
Aisling (Irish): dream
Magia (Latin): magic
Aisling (Irish): dream
Blog post ini dibuat dalam rangka mengikuti Kompetisi Menulis Cerpen #MyCupOfStory Diselenggarakan oleh GIORDANO dan Nulisbuku.com